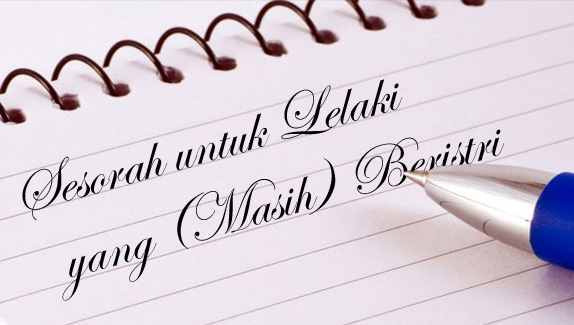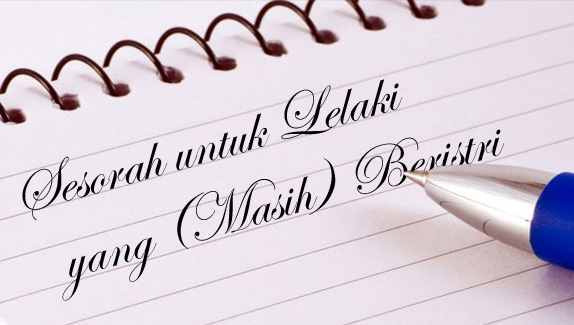Kupenuhi ajakannya per telpon untuk makan malam di sebuah kafe mewah yang belum pernah kujamah. Katanya ada sebuah pekerjaan yang membutuhkan diriku. Kubayangkan dia akan meminta bantuanku menulis biografi atau buku jagad lukisan. Itulah yang paling mungkin kulakukan, walaupun belakangan ini cenderung bermalas-malasan.
Ternyata di luar dugaanku. Setelah berbasa-basi seperlunya dia pun melepas niatnya dengan gaya bicaranya yang lugas. Ceplas-ceplos.
“Bung, kami akan bikin Kawin Perak. Kupikir-pikir penting juga pernik-pernik kehidupan seperti itu. Bertahan seperempat abad sebagai suami-isteri ternyata sebuah keberhasilan yang perlu disyukuri. Bung sendiri sudah bikin Kawin Perak dengan sebuah buku. Nah, kami kepengin yang lain. Apa bentuknya sedang digarap Nyonya. Yang jelas, kami sepakat mengisinya dengan ceramah. Tapi tidak mengundang ustad, kiai, atau pakar ilmiah. Topiknya kesiapan mental menduda.”
Dan tanpa menunggu tanggapanku, dia pun melanjutkan kalimatnya.
“Jangan protes dulu, Bung. Biarkan saya ngomong.”
Aku pun mengalah dan membiarkan dia membakar kreteknya. Kemudian kudengar rentetan kata-katanya yang semrawut.
“Biasanya seorang ustad atau kiai bicara normatif. Idealistis. Dogmatis. Dan rujukannya sudah jelas ayat-ayat suci Al Quran atau kisah-kisah Rasulullah. Yang itu boleh dibilang sudah sering kudengar di banyak pengajian. Pakar ilmiah pasti bicara teoretis. Rumit. Njelimet. Muluk-muluk. Argumentasinya berkepanjangan. Yang awam biasanya tak betah mendengarnya. Kami kepengin dengar sesorah yang empiris. Yang konkret. Yang realistis. Yang sederhana. Rujukannya kita sendiri. Sesama manusia. Artinya punya benar dan salah. Setuju, bukan?”
“Boleh juga.”
“Ini penting, Bung. Sebab, kami sudah memilih Bung sendiri yang sesorah.”
“Apa dasarnya?”
“Sederhana saja. Ndilalah Bung harus menjadi duda dadakan. Nah, kami kepengin dengar pengakuan Bung mengendalikan kehidupan. Biar jadi rujukan bagi kita-kita yang masih normal. Setuju, bukan?”
“Wah, sontoloyo sampeyan. Tapi menantang. Jadi, bolehlah dicoba. Terus, apa yang mesti kusampaikan?”
“Itu terserah Bung. Yang jelas, kami mengundang dua puluh lima pasangan suami-isteri yang terpilih dari sekian banyak kerabat dan sahabat. Tempatnya restoran termahal di kota tercinta yang terseok-seok ini. Jadi, Bung tak perlu sungkan-sungkan bicara, lantaran publiknya sudah pilihan.”
“Sampeyan ini kayak orang kuker, ya?”
“Apa itu kuker?”
“Kurang kerjaan. Tapi ndak apa-apa, wong duit sampeyan turah-turah. Lantas, berapa honor saya? Ini profesional, bukan?” ujarku sekedar berseloroh sembari melolos sebatang kreteknya yang dibilang kualitas ekspor. Kemudian kusempatkan sekejap mengerling wajah-wajah perempuan yang kebetulan melintas di dekat kami.
“Cantik-cantik?” katanya lirih seperti hendak membaca pikiranku.
“Boleh juga. Tapi sampeyan harus bilang lebih cantik isteri sendiri.”
“Mungkin saya mesti bilang demikian. Tapi sudahlah. Nanti Bung sakit hati.”
“Tidak. Tak ada masalah.”
“Syukurlah. Saya yakin Bung sudah matang.”
“Kok tahu?”
“Rasa-rasanya begitulah.”
Percakapan kami terhalang hadirnya sepasang pelayan remaja yang sibuk mengemas hidangan. Dan sekejap kemudian kudengar ujaran sahabatku.
“Saya harap selera Bung berkembang.”
“Terima kasih. Sekarang memang cenderung malas makan di rumah. Rasanya sepi dan cemplang.”
“Saya paham. Pasti jauh bedanya dengan yang dulu. Soalnya beliau mahir sekali memasak.”
“Di bidang itu boleh dibilang pilih tanding. Apa pun yang disentuh pasti jadi hidangan yang nikmat. Dulu makan itu sebuah kesibukan yang indah, asyik, seni, gairah, dan semangat. Sekarang sepi. Cemplang. Kosong. Sebab makan hanya karena lapar. Jadi, kesempatan macam ini jelas menyenangkan.”
“Syukurlah. Ayo, sikat habis, Bung.”
Kami pun lantas sibuk dengan piring masing-masing. Dan di celah kesibukannya kudengar lagi kalimatnya yang renyah.
“Begini, Bung. Belakangan aku berpikir, suami-isteri mana pun harus bersiap mental untuk sewaktu-waktu menjadi duda dan janda dadakan Iya kan? Siapa yang tahu persis jadwal kematian kita sendiri? Saya bisa bayangkan apa yang Bung rasakan. Tiba-tiba ditinggal istri dengan kematian yang sangat mendadak. Kalau orang berpisah karena usia lanjut atau sakit berkepanjangan, barangkali kesiapan mentalnya sudah berkembang. Lain sama Bung. Pasti tanpa persiapan, bukan? Nah, kelanjutannya bisa jadi bahan kajian yang menarik buat psikolog seperti Pak Darmanto Jatman atau Bu Frieda yang centil. Tapi biarlah.”
Terlintas wajah Pak Darmanto Jatman yang simpatik dan Bu Frieda yang ramah. Mungkin benar pikiran sahabatku. Tapi, biarlah. Buat apa menawar-nawarkan masalah. Aku sendiri merasa belum punya problem serius dengan statusku sebagai seorang duda dadakan. Tanpa secuil pun rencana dan niatan. Jangankan rencana, membayangkan selintas pun tak pernah.
Rencana kami serumah justru merangkai kembang-kembang kegembiraan untuk pernikahan gadisku yang sulung. Sudah sekian lama kami pun sibuk merancang dan meracik berbagai keperluan pestanya. Sudah memilih hari yang baik. Sudah menghitung-hitung undangan. Sudah memilih-milih menu hidangan. Sudah memesan gedung. Sudah merancang rias, busana, cenderamata, dan macam-macam. Pokoknya, sudah segalanya. Sudah total. Sudah tuntas.
Tapi segalanya terpaksa buyar berantakan seperti disambar halilintar lantaran Sang Pemilik Kehidupan telah memanggil pulang istriku dengan sangat mendadak dalam sebuah adegan yang setitik pun tak pernah terbayangkan dalam rancangan skenario kehidupanku sendiri.
Peristiwanya berlangsung teramat singkat di tengah perjalanan ke tanah kelahiran untuk sebuah acara kondangan.
Di sebuah tikungan mobil kami harus berhenti karena kemacetan yang panjang. Tiba-tiba pantatnya tersodok mobil dari belakang. Setelah menepi ke bahu jalan, kami pun turun untuk menyaksikan luka mobil kami sendiri. Ternyata hanya penyok sedikit bempernya, sehingga aku sendiri tak berniat menciptakan perkara. Sambil meyakini posisiku yang benar, kubiarkan mobil yang menabrak itu melintasi kami. Kupikir akan terus melaju, ternyata berhenti agak jauh di depan.
Saat kami berkemas, datanglah sopirnya yang berniat mempersalahkan kami dengan dalih berhenti mendadak. Tentu saja aku bertahan dengan kemantapan sepenuh hati. Meskipun samar-samar kulihat mobil itu bernomor dinas militer, tak berkurang setitik pun niatku mempertahankan kebenaran. Kudengar permintaan istriku untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan samar-samar kudengar juga pembenaran orang-orang setempat yang bermunculan merubungku.
Tiba-tiba kusaksikan istriku terkulai di bahu jalan. Kontan saja kulepas perhatianku untuk menuntaskan percakapan. Lantas dalam sekejap kusaksikan orang-orang itu sudah menjunjung istriku dan membawa masuk ke rumah terdekat buat pertolongan darurat. Berhubung tanda-tanda kesadarannya makin menghilang maka segera kularikan ke rumah sakit, tetapi jiwanya tak tertolong.
Kata dokter, isteriku mengalami keterkejutan yang mendadak akibat benturan mobil dari belakang. Kemudian tekanan darahnya melonjak cepat sehingga terjadi pendarahan di kepalanya. Dokter pun bilang kematian almarhumah indah sekali. Khusnul khotimah. Kemungkinan lain justru akan menimbulkan kesulitan yang berkepanjangan seperti stroke, lumpuh, matisuri dan semacamnya.
Kami serumah sudah ikhlas melepas kepergian almarhumah tercinta, walaupun kadang masih menahan dendam terhadap penyebabnya. Kadang kami pun berharap sopir itu kelak mengalami kemalangan yang berlebihan. Tapi, siapakah orangnya? Entahlah. Hanya Gusti Allah yang melihatnya.
Biarlah dia merasa terbebas dari kesalahannya. Biarlah dia berlari ke seluruh penjuru jagad. Biarlah. Dan biarlah Kehidupan Yang Agung menghukumnya dengan keadilan yang akurat. Mungkin pembiaran itu tidak rasional. Tapi apa yang bisa kuperbuat? Sudah kutulis surat pembaca di koran-koran dengan harapan ndilalah terbaca pihak-pihak yang bersangkutan. Siapa tahu sampai juga ke sopir itu dan terketuk nuraninya untuk meminta maaf. Sebatas itu pun akan sangat melegakan hati kami serumah. Tapi, sudahlah.
Yang jelas, sekarang terasa alur jagad kecil kami berubah. Meskipun sudah bertekad lebih berpikir ke depan, ternyata lintasan masa lalu mustahil dihapuskan. Dan muncullah berbagai masalah keseharian yang tak selalu gampang dirampungkan sendirian. Kalaupun konsultasi ke psikolog, paling banter jawabnya hanyalah anjuran dan saran yang sangat teoretis. Lagi pula siapa yang menjamin para psikolog itu sehat lahir batin?
“Bung, maaf, boleh saya bertanya?” ujar sahabatku memotong lintasan pikiranku sembari menawarkan kembali kreteknya yang mahal setelah kami tuntas melahap segenap menu hidangan.
“Kenapa tidak?” jawabku ringan.
“Pernah terlintas Bung kepengin protes kepada Gusti Allah?”
“Pikiran seniman memang kadang gila-gilaan. Kalau sampeyan seorang ustad, pasti ngomongnya lain. Yang sering kudengar: tabahlah, kuatlah, ikhlaslah, lapanglah, pasrahlah, dan sebangsanya. Selanjutnya mereka bilang setiap lelakon pasti ada hikmahnya, ada misterinya, ada rahasianya yang tak selalu kita mengerti dalam sekejap. Tapi pikiran sampeyan edan tenan.”
“Lho, katanya seniman mesti kreatif. Maaf, kalau Bung tersinggung.”
“Tidak, biasa saja.”
“Lantas gimana jawabnya.”
“Mungkin bukan protes, tapi bertanya. Apa to misterinya? Apa to rahasianya?”
“OK. Jawabnya memang bukan di tangan kita. Sekarang yang konkret saja, Bung. Apa problem keseharian yang berkembang?”
“Wah, panjang jawabnya. Bisa jadi sebuah makalah. Atau cerpen. Atau novel.”
“Itulah kelebihan Bung. Bisa menyalurkan beban derita batinnya sendiri. Tapi itu soal lain. Sekarang saya kepengin dengar sedikit saja problem seorang duda dadakan. Biar saya yakin pilihan masalah itu memang relevan dengan rencana kami. Artinya, nanti saya bisa bilang sama istri di rumah, ceramah Bung tidak kalah hebatnya dengan seminar-seminar nasional.”
“Edan tenan sampeyan. Tapi baik juga.”
“OK. Lantas? What next?”
Ternyata aku tak mampu segera memenuhi harapannya. Terlalu banyak yang ingin kukatakan. Segalanya berdesakan. Gemuruh. Penuh. Kebak. Mampet. Sumpek. Dan macet.
Aku pun terdiam. Lantas kubiarkan gagasanku melesat menembus malam. Kubiarkan sahabatku termangu bersama kepulan asapnya. Kubiarkan para pengunjung kafe itu terheran-heran menyaksikan diriku sudah dirubung ratusan perempuan yang cantik-cantik. Jangan tanyakan apakah mereka gadis-gadis, setengah gadis, setengah janda, janda-jandaan, dan janda betulan. Entahlah. Aku sendiri tak paham. Dan tak kepengin memahaminya. Yang kulihat, rambut mereka tergerai dipermainkan angin. Tangan dan kakinya melambai-lambai seperti selendang bidadari dalam dongeng-dongeng fantastik. Wanginya semerbak menghias langit dan senyumnya bertebaran ke bumi yang kelam. Gaun mereka berwarna-warni seperti pelangi alam yang sering dinyanyikan bocah-bocah sekolah. Semarak dan meriah. Mirip karnaval. Tapi tak seorang pun yang menyapa diriku.
Kami pun melanglang jagad, menembus langit, melintasi gunung-gunung dan laut. Jauh, jauh sekali. Kulintasi puncak Ungaran yang bongkok, Kendalisodo yang mungil, Merbabu yang gemuk, Merapi yang sombong, terus ke Laut Selatan yang garang. Lantas kulihat dari kejauhan wajah Jogja yang temaram, terus ke Sindoro-Sumbing yang anggun, dan dalam sekejap sudah kembali kulintasi Semarang yang gemerlapan.
Malam itu Semarang dalam gengggamanku. Kurasakan seluruh denyut kehidupannya. Kudengar samar bisik-bisiknya, keluh-kesahnya, nyanyiannya, tangisnya, dan kulihat polah-tingkahnya yang jumpalitan. Di celah-celah mereka tampak sahabatku Triyanto Triwikromo sedang rerasan dengan isterinya. (“Wah, makin susah mengarang cerpen. Habis, setiap saat dikejar-kejar dead line pemberitaan”). Sebentar kemudian kusaksikan Eko Budihardjo sibuk menulis artikel “Gayeng Semarang” di samping istrinya yang santai melahap sebuah novel. (“Aduh, kerepotan Rektor mulai terasa. Orang pun masih bertanya-tanya soal titipan UMPTN. Kubilang tegas, tak ada jalur titipan. Tapi, siapa menjamin?”). Di tempat lain tertangkap senyuman Gunoto Saparie dalam dekapan istrinya yang ramping. (“Sabarlah, kapan-kapan kita kredit sebuah mobil. Yang sudah hilang, sudahlah. Tuhan selalu mendengar doa dan harapan kita. Biarlah malingnya bersenang-senang sejenak. Hatinya pasti gelisah berkepanjangan.”)
Penyair Gunoto Saparie memang pernah kehilangan mobil saat parkir di halaman kantor gubernuran. Terbayang sekejap betapa kagetnya, betapa bingungnya, betapa sedihnya, betapa repotnya sang penyair. Tapi batinku berbisik, Gun, repotmu masih bisa ditebus dengan uang. Dan masih punya seorang perempuan yang selalu pasrah dirangkul buat rerasan. Jagalah baik-baik sebelum terampas dari rangkulanmu. Lagi pula jangan berniat merangkul-rangkul yang lain. Kulihat penyair Gunoto Saparie terkesiap sejenak. Barangkali heran mendengar samar rerasanku yang jauh. Padahal di kamarnya hanya berduaan, karena sepasang bocahnya sudah merakit mimpi di kamar yang lain. Lantas dia pun merapatkan dekapannya seperti ketakutan membayangkan wajahnya sendiri. Untunglah perempuan itu bukanlah titisan Setiawati dalam legenda Anglingdarma yang sedang populer di layar sinetron.
Suatu saat Prabu Anglingdarma tersenyum lembut mendengar rerasan sepasang cicak yang cemburu menyaksikan kemesraannya mencumbu Setiawati. Kesaktian Anglingdarma yang bisa berdialog dengan bahasa hewan apa pun menjadikan perempuan itu pun merajuk dan kepengin sekali ikut menggenggam ilmunya sang suami. Padahal kesaktian itu terlarang diajarkan kepada siapa pun, termasuk untuk istrinya sendiri. Tapi perempuan Setiawati sulit memahami sumpah sakti suaminya, bahkan mengancamnya dengan pati obong. Namun, kecantikannya yang tanpa tandingan itu ternyata bukan jaminan buat merobohan keteguhan janji suaminya. Dan akhirnya Sang Prabu Anglingdarma lebih merelakan kematian isteri tersayang ketimbang melanggar sumpah saktinya sendiri.
Barangkali Mas Angling memang sudah bersiap mental menjadi seorang lelaki duda yang harus konsekuen dengan segala akibatnya. Kemungkinan lain, terbayanglah kemudahan-kemudahan seorang raja besar yang kapan pun justru dirindukan dan dilamar perempuan. Tapi kelanjutan kisahnya ternyata bukanlah lelakon yang serba menyenangkan. Lelaki tampan, kaya, dan berkuasa itu pun malahan meninggalkan tahtanya yang gemerlapan dan memilih pengembaraan yang jauh buat memburu semangat kehidupan.
Edan, Mas Angling, batinku sendirian. Di manakah sampeyan sekarang? Ternyata tanpa jawaban siapa pun. Dan sadarlah aku masih terpaku di kursiku sendiri. Ke manakah sahabatku? Kupikir paling banter ke kamar mandi. Atau sedang ke kasir. Biarlah.
Perlahan kucabut lagi sebatang kretek dari bungkusnya yang tergolek sepi. Tapi muncul keraguan hendak membakarnya. Terbayang apiku bakal menjilat-njilat langit seperti pati-obongnya Setiawati. Dan aku pun merinding membayangkan perempuan cantik-cantik di kafe yang mewah itu pada hangus terpanggang tanpa sesambat. Lantas terdengar samar keluhan Mas Anglingdarma yang mengutip baris-baris terakhir sajaknya Goenawan Muhamad tentang keraguan dirinya terhadap percintaan sejati.
“Batik Madrim, Batik Madrim, mengapa harus, patihku? Mengapa harus seorang mencintai kesetiaan lebih dari kehidupan dan sebagainya dan sebagainya?”
Edan, ternyata Mas Angling mahir juga bersajak. Aku pun ingat judulnya “Dongeng Sebelum Tidur.” Terakhir kubaca di buku Asmaradana terbitan Grasindo Jakarta sekian tahun yang lewat.
Perlahan melintas wajah sejawat Pamusuk Eneste yang telah memesan karanganku tentang novel-novel Ahmad Tohari. Sudah setengah jalan kerjaku saat musibah itu terjadi sekian bulan yang lewat. Kemudian tersendat-sendat, bahkan terbilang macet total. Untunglah, Pamusuk Eneste bisa memahami kesulitanku.
Tapi aku sendiri harus menata kembali semangat kepengaranganku yang nyaris berantakan. Kepercayaan Grasindo yang terkenal itu harus segera kutebus dengan prestasi yang maksimal. Tapi, sampai kapan?
“Yang penting mencoba dan mencoba lagi,” sahut Mas Angling entah di mana.
“Sampeyan pernah mengarang, Mas Angling?” tanyaku berseloroh.
“Saya paham, mengarang itu gampang-gampang-sukar,” jawabnya samar.
“Sampeyan senang bersajak?”
“Sajak yang baik adalah ruh kehidupan. Jadi, siapa pun sebaiknya senang bersajak.”
“Sampeyan paham betul maksud sajak Goenawan Mohamad?” tanyaku lirih.
“Ndilalah saya sendiri yang dikisahkan. Dan ingatlah, kehidupan yang abadi tak mengenal hitungan jarak dan waktu. Saya sudah menyaksikan peta kehidupan yang panjang, dan akan terus menyimaknya hingga zaman berakhir. Tentu saja dengan caraku sendiri.”
“Apakah sampeyan paham juga pergulatan batinku?” ujarku setengah penasaran.
“Sekurang-kurangnya saya bisa menjadi prasasti kehidupan.”
“Lantas, apa saran dan usul sampeyan?”
“Sesungguhnya pemahaman yang paling mendalam hanyalah dari diri sendiri. Sang Guru Sejati telah bertahta dalam setiap pribadi. Bicaralah dengan bijaksana.”
“Maaf, sampai di sini dulu Mas Angling. Aku pun pening.”
Tak terdengar jawaban Mas Angling yang mendadak lenyap dari pandanganku. Kemudian muncul kembali sahabatku dengan wajahnya yang semringah.
“Sorry, Bung. Tadi kutinggal sebentar. Ndilalah ketemu relasi bisnis. Cantik-cantik lho. Mau kenalan? Siapa tahu kita dapat proyek barengan. Soal sesorah, pikirkan kapan-kapan. OK?”
Tentu saja aku pun kontan sepakat.
Dan selanjutnya, silahkan pembaca yang bijak-budiman membayangkan sendiri-sendiri naskah sesorahku. Entah kapan, dan entah di mana.
Tancep kayon.***
(Semarang, Juni 2001)
Tulisan diterbitkan :
1. Wawasan
2. Buku kumpulan Cerpen “SESORAH UNTUK LELAKI YANG (MASIH) BERISTRI” oleh Yudiono KS